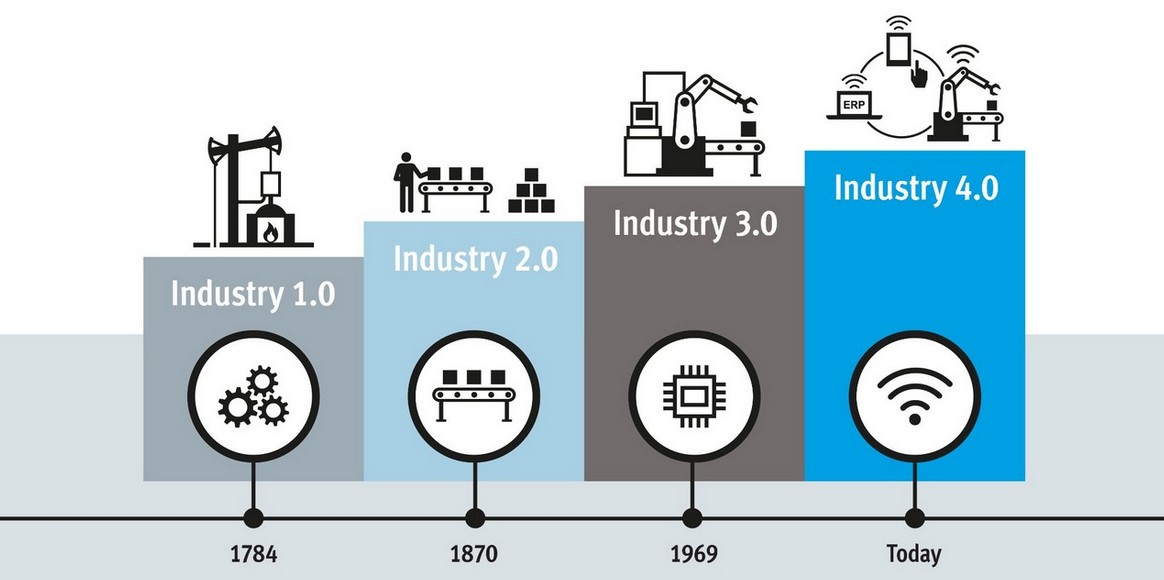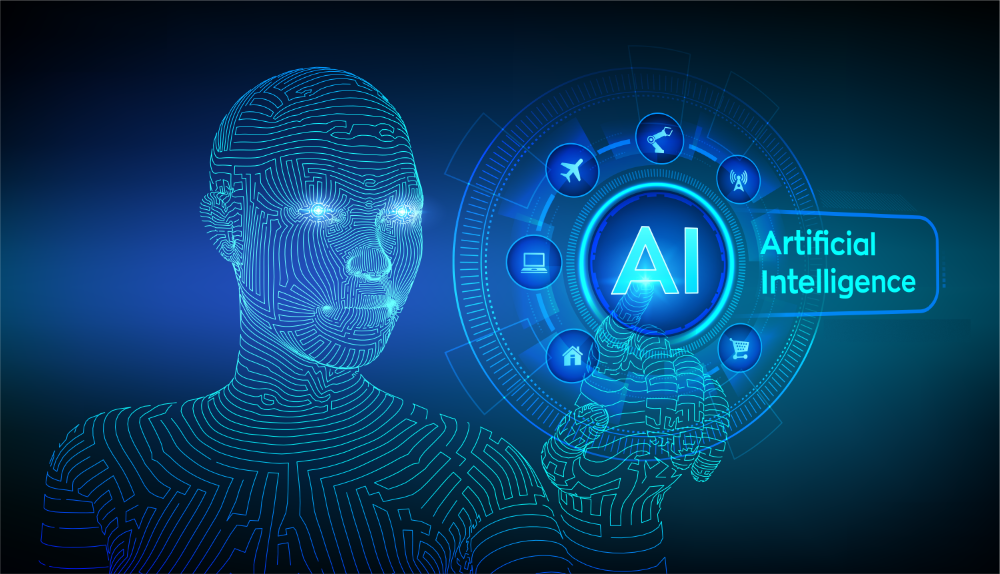Lanjutan 3… Kopi di Kerintji
Dalam tradisi masyarakat dataran tinggi Kerinci, daun kopi di kenal dengan “Minun Kawoa”, Kawoa atau Kawa untuk pengertian masyarakat Kerinci adalah Kopi Daun, Daun Kopimuda yang sudah melalui proses penjemuran dan pengasapan. Kemudian diseduh di dalam tabung kawoa, yang terbuat dari bambu betung tua dan pegangannya dari kayu sigi (Pinus Strain Merkusi) atau kayu Pacat endemik Kerinci, serta di minum di batok kelapa di campur gula enau (Aren).
Kalau di tilik dari tradisi minun kawoa tanaman kopi sudah ada di Kerinci sejak abad ke 14 mungkin bisa jadi diatas abad 14, kenapa penulis mengatakan tradisi minun kawoa sudah ada sejak abad 14, sesuai temuan tabung kawo di dusun Sungai Penuh, yang menurut antropolog Leiden University Dr. Jet Bakels, yang meneliti di Kerinci tahun 1992-1996, ragam hias di tabung kawoa tersebut sama dengan ragam hias temuan gerabah dan arsitektur traditional Kerinci, tapi yang pastinya belum ada uji karbon atau carbon dating tentang ini.
Hubungan motif atau ragam hias “tabung kawoa” dengan temuan arkeologi dari zaman perunggu, ada baiknya sedikit kita ulas tentang kebudayaan perunggu ini, bukti arkeologi menunjukkan bahwa artefak logam tertua ditemukan di Turki yang diperkirakan berasal dari tahun millennium ke 6 SM (Haryono, 2001: 2). Sementara itu, di Asia Tenggara zaman logam diperkirakan di mulai pada tahun 2000 SM. Hal ini berdasarkan pada tinggalan-tinggalan produk budaya bendawi berupa artefak logam perunggu yang ditemukan di Thailand (Haryono, 2001). Van-Heekeren (1958:1) mengemukakan bahwa di Indonesia tidak dikenal adanya zaman tembaga atau zaman perunggu karena temuan perunggu di Indonesia pada umumnya terdapat pada lapisan yang sama dengan temuan besi, karena itu dia menggunakan terminologi zaman perunggu-besi untuk menyatakan zaman logam di Indonesia.
Heekeren juga berpendapat bahwa kebudayaan perunggu Indonesia berasal dari luar yaitu dari Dong Son, wilayah Vietnam Utara saat ini. Para ahli berbeda pendapat dalam hal ihwal kapan dimulainya zaman perunggu di wilayah Dong Son, namun H. Geldern menduga bahwa masa perunggu Dong Son di mulai sekitar abad ke-8 dan ke-7 SM (Haryono, 2001: 50). Berbagai bentuk budaya Dong Son telah diimpor ke Nusantara di masa perundagian, baik itu yang sifatnya bendawi maupun ilmu pengetahuan dalam teknik pembuatannya. Menurut Hoop (1932) masuknya logam di Indonesia diperkirakan pada tahun 500-300 SM.
Di antara artefak logam temuan Indonesia yang menunjukkan ciri kentara pengaruh kebudayaan Dong Son adalah nekara perunggu, kapak perunggu, patung perunggu, dan bejana perunggu. Pada masa selanjutnya artefak perunggu sudah diproduksi secara lokal seperti contohnya nekara tipe pejeng ataupun moko yang ditemukan di Bali dan Nusa Tenggara Timur (Bintarti, 2001). Bejana perunggu salah satu produk budaya bendawi masa perundagian, telah menjadi objek peneilitian menarik dalam ilmu arkeologi. penelitian yang berkembang hanya menyangkut aspek teknis untuk mengetahui bagaimana bejana dibuat pada masa silam atau lebih menekankan analisis bahan dengan pendekatan saintifik untuk melihat bagaimana persamaan komposisi bahannya dengan artefak perunggu lainnya yang dihubungkan dengan paradigma difusi. Sayangnya, dari sisi keartistikan dan estetika dengan berbagai motif indah pada permukaan bejana sedikit sekali peneliti yang berminat untuk mengkajinya.
Haffiful Hadi Suliensyar dalam kajian ragam hias bejana perunggu di Kerinci menyatakan : dalam pola dan ragam hias yang ada pada bejana menunjukkan ciri khusus yang ada padanya. Van-Heekeren (1958) mencatat bahwa kajian-kajian terhadap bejana perunggu yang telah dilakukan pada saat itu hanya terbatas pada deskripsi bentuk, motif hias dan teknik pembuatannya saja. Analisis bahan hanya dilakukan pada satu objek bejana saja yaitu yang ditemukan di Asemjaran, Madura. Sementara itu, Sumardjo (2002) pernah melakukan penafsiran terhadap makna pola hias bejana perunggu Kerinci secara hermeneutis-historis. Setelah itu, penulis belum menemukan referensi tentang kajian-kajian berikutnya dengan objek bejana perunggu tersebut. Ahimsa-Putra (1999a) dalam artikelnya telah menawarkan cara baru dalam mengupas masalahmasalah arkeologi terutama arkeologi semiotik, yaitu melalui pendekatan strukturalisme LeviStrauss. Lebih lanjut Tanudirjo (2016) mengemukakan bahwa analisis struktural mencoba menemukan prinsip-prinsip dasar pikiran manusia sebagaimana yang tertuang dalam unsur budaya dominan seperti pola perkampungan, pola hiasan, kekerabatan mitos dan lainnya.
-- (Artikel 4) --